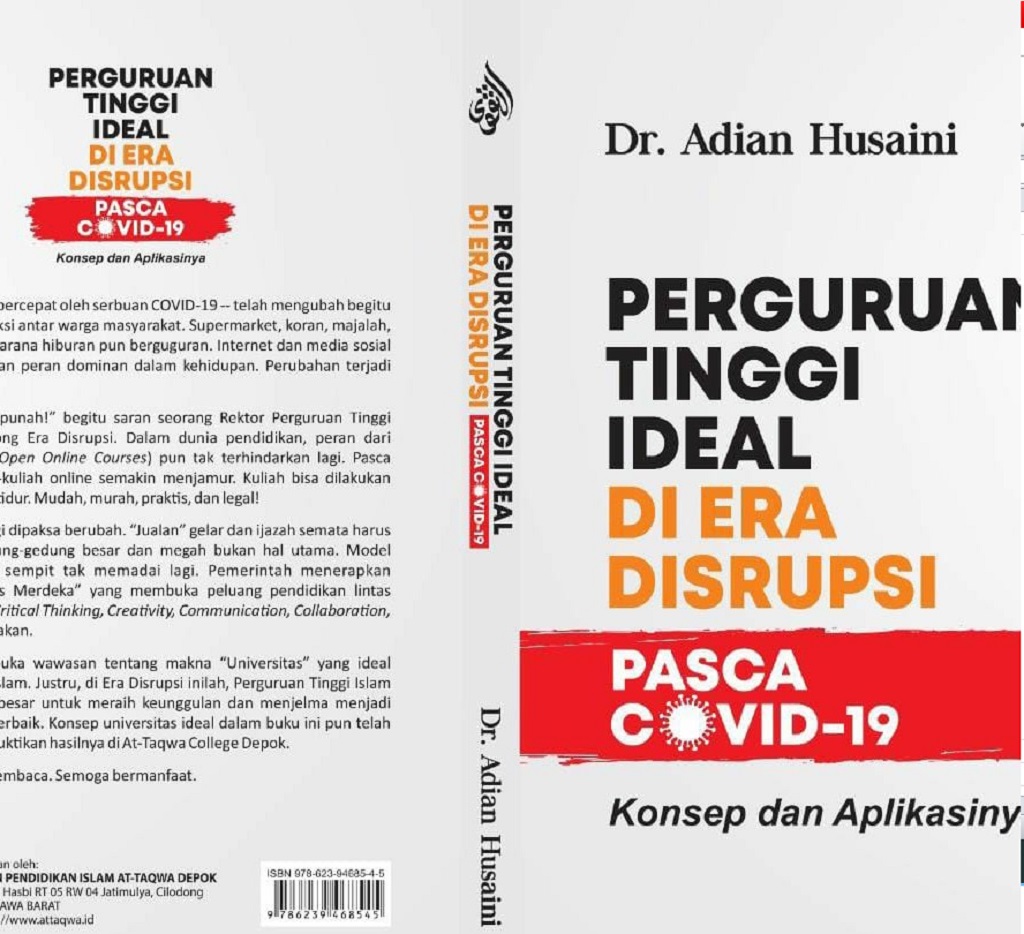Oleh: Dr. Adian Husaini (www.adianhusaini.id)
Alhamdulillah, pada 17 Desember 2020, telah dilaksanakan diskusi dan peluncuran buku “Perguruan Tinggi Ideal di Era Disrupsi pasca COVID-19” cetakan kedua (Depok: YPI at-Taqwa, 2020). Diskusi ini dihadiri sekitar 300-an peserta, melalui media Zoom dan FB.
Disamping peserta individual, ada beberapa mahasiswa Akademi Da’wah Indonesia (ADI) Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia, yang menyelenggarakan “nonton-bareng” (nobar). Tampak ADI Palu, ADI Jawa Barat, ADI Bengkulu, ADI Bukittinggi, dan sebagainya. Tampak juga peserta yang merupakan mahasiswa S3 Pendidikan Islam UIKA Bogor.
Satu poin penting yang saya tekankan pada diskusi tersebut adalah menjelaskan kembali makna “universitas” dan “Pendidikan Tinggi” dalam Islam. Sebab, dalam wacana sehari-hari, dua istilah penting itu telah banyak disalahpahami. Seperti juga kesalahpahaman terhadap makna “Pendidikan” dan “sekolah”.
Hakikat “Pendidikan” adalah penanaman nilai-nilai kebaikan dalam diri seseorang (TA’DIB). Jadi, bisa saja seorang secara formal tercatat dan ikut sebagai murid di satu sekolah, tetapi ia tidak berpendidikan. Sebab, ia tidak menjalani proses penanaman nilai-nilai adab atau akhlak mulia. Ia bersekolah, tetapi tidak berpendidikan.
Begitu juga halnya dengan makna “Pendidikan Tinggi” dan “Perguruan Tinggi”. Bisa jadi, seorang mahasiswa tercatat dan mengikuti proses perkuliahan di suatu universitas, tetapi pada hakikatnya, ia tidak berpendidikan tinggi. Sebab, dalam istilah Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas, ia tidak menjalani proses Pendidikan untuk menjadi manusia yang sempurna (al-insan al-kulliy/ a universal man).
Saat ini, di dunia internasional, universitas telah disempitkan maknanya menjadi tempat untuk “men-training” mahasiswa agar meraih wawasan dan skill tertentu, untuk bisa mencari makan dan meraih kedudukan sosial tertentu. Mahasiswa tidak dididik menjadi “orang baik”; yakni – menurut UUD 1945 pasal 31 (3) – manusia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia.
Jadi, betapa banyak orang salah paham tentang makna “universitas” dan “Pendidikan tinggi”. Karena itulah, tidak heran, jika banyak mahasiswa yang ikut kuliah, tetapi akhirnya ia tidak “berpendidikan tinggi”. Ia tidak paham tentang hakikat dirinya, tentang hakikat Tuhannya, tidak paham tujuan dan tugas hidupnya, tidak paham makna ilmu, tidak paham bagaimana beradab kepada para nabi dan para ulama, tidak paham bagaimana bersikap terhadap orang tuanya, guru-gurunya, saudara-saudaranya, dan juga tidak paham bagaimana bersikap terhadap negaranya secara adil.
Dan bahkan ia tidak paham bagaimana harus bersikap terhadap dirinya sendiri; bagaimana memperlakukan jiwa (nafs) dan badannya secara adil; bagaimana ia harus menempatkan proses “pensucian jiwa” (tazkiyyatun nafs), sebagai kegiatan terpenting dalam hidupnya!
Ringkasnya, meskipun menjalani proses perkuliahan, tetapi si mahasiswa tidak dididik untuk menjadi manusia seutuhnya, yakni dididik menjadi “orang baik” (good man), dididik sebagai hamba Allah dan khalifatullah fil-ardl, sebagaimana tujuan penciptaan dirinya. Bahkan, sejak di bangku sekolah, ia sudah diajarkan, bahwa asal-usul dirinya berasal dari kelanjutan kehidupan monyet, dan tujuan terpenting dari proses pendidikannya adalah bisa meraih “survive” dalam kehidupan secara materi. Dan bahwa kemajuan terpenting dalam hidup adalah meraih jabatan tinggi, meraih popularitas, meraih kekayaan materi, dan sejenisnya.
Padahal, dalam konsep dan sejarah Pendidikan Islam, Perguruan Tinggi (Universitas) adalah tempat untuk mendidik manusia menjadi “al-insan al-kulliy”, menjadi manusia yang seutuhnya, atau manusia yang universal. Proses Pendidikan tinggi itu bisa berlangsung di rumah, di masjid, di Pesantren Tinggi, di Universitas Islam, dan sebagainya. Yang penting disitu terjadi proses “pendidikan tinggi”, bukan sekedar ada bangunan universitas dan proses perkuliahan secara formal.
Lanjut baca,